Bagai Pungguk Menjerat Bulan Part 3
- account_circle admin
- calendar_month Ming, 16 Jul 2023
- visibility 207
- comment 0 komentar

PCNU-PATI Photo by Pawan Thapa
Oleh : Elin Khanin
Akhirnya, setelah insiden itu, Salman menemukan alasan untuk bertahan hidup di pesantren. Apalagi kalau bukan karena Bu Nyai Maryam—perempuan pemilik kecantikan di atas rata-rata. Bahkan mungkin setiap inchi darinya adalah dambaan setiap wanita. Body S-line, wajah V-line, kulit seputih kapas, mata bulat dengan dua lipatan kelopak mata, hidung tinggi tapi kecil, kening yang agak menonjol dan bibir merah alami. Sepertinya standar kecantikan para Ratu Joseon sudah diborong dia semua. Bagaimana Salman, atau mungkin santri cowok lainnya tidak tertawan? Mereka bungkam hanya tidak berani saja karena Bu Nyai Maryam adalah istri dari Kiai mereka. Sekali pun istri kedua, Bu Nyai Maryam adalah perempuan yang harus mereka hormati dan patuhi.
Awalnya Salman sempat berontak karena merasa tidak adil, mengingat kakak lelakinya ….
“Kak Yujin dulu nggak masuk pesantren, kenapa sekarang aku dimasukkan ke pesantren?”
Masih lekat dalam ingatan Salman, perdebatan dengan Mommy-nya di malam sebelum berangkat ke pesantren Al-Mukmin. Sebenarnya tidak hanya malam itu, tapi hampir setiap hari perdebatan demi perdebatan mewarnai hari-hari Salman. Bahkan sejak ia masih duduk di bangku SMP dan SMA, Mommy-nya sudah berniat memasukkannya ke pesantren. Berbagai referensi ditawarkan. Mulai dari Assalam Solo, Darussalam Gontor, Darul Quran milik Yusuf Mansyur, Mathaliul Falah Kajen, hingga Lirboyo. Tapi jawaban Salman tetap sama. “Mommy mau buang aku ya? Kenapa nggak sekalian dibuang ke panti asuhan aja?”
Nah kan, itu bibir memang perlu diplester.
“Risi, banyak faktor yang melatarbelakangi kenapa Kak Yujin nggak dimasukkan pesantren. Salah satunya Kak Yujin kan gampang sakit, jadi ….”
“Jadi karena aku jarang sakit, aku yang harus mondok? Ya udah, aku tak sakit-sakitan aja,” potong Salman dengan muka rusuh. Ia meremas-remas jarinya kalut. Ada rasa nyeri yang bersekutu di dadanya.
“Kok gitu? Sehat itu adalah rezeki paling utama kok, malah—”
“Ngebet banget emang Mommy mau buang aku. Kenapa nggak dibuang ke panti asuhan aja?” Dan jawaban klise itu meluncur lagi. Tapi Mommy sudah terbiasa kok. Jadi, dia hanya tersenyum dan melontarkan respon yang sama juga. “Kamu bukan yatim piatu, kenapa harus dimasukkan ke panti asuhan? Mommy cuma pengen punya anak yang tahu agama. Kalau Kak Yujin nggak sakit-sakitan, dia juga pengen masuk ke pesantren. Buktinya sekarang juga mau ikut ngurus pesantren sekaligus perusahaan Opa.”
“Kalau aku nggak mau, Mommy mau apa?”
Perempuan paruh baya yang duduk di sampingnya terdiam, mencoba memberi jeda sebelum kembali melancarkan bujuk rayunya. Dia tidak mau menyerah kali ini.
“Risi, ini adalah amanah Opa. Salah satu cicitnya ada yang menguasai ilmu agama dan bisa menjadi pemimpin ….”
“Aku nggak mau. Kan aku udah bilang kalau aku pengen jadi dokter kayak Mommy.” Lagi, Salman memotong ucapan Mommy-nya. Ya, bagi Salman, Mommy adalah role modelnya. Sedari kecil dia sangat mengagumi bagaimana Mommy-nya mengenakan sneli dan scrub, memainkan jarum suntik dan pisau bedah, bagaimana Mommy-nya berperang di kamar operasi, dan melayani pasien di IGD. Semuanya membuat Salman terpukau. Sehingga ia bertekad kelak ingin menjadi seperti Mommy-nya. Dan tekad itu semakin kuat saat tahu berkat orang-orang seperti Mommy-nya, Daddy-nya bisa bertahan hingga sekarang.
“Kamu tetep bisa kok jadi dokter meski masuk ke pesantren. Menjadi santri tidak akan membuat cita-citamu terbengkalai. Bahkan sudah banyak orang-orang besar yang background-nya adalah santri. Santri itu justru bisa apa saja. Keren kan kalau ada dokter yang hafal Al-Quran. Dokter Al-Hafidz. Duh, Mommy pengen banget deh punya anak kayak gitu. Pasti ntar cewek-cewek pada antri,” tukas Mommy dengan pasang mata yang sedikit berembun.
“Nggak santri aja banyak yang antri,” sanggah Salman.
“Apalagi santri.” Dan Mommy berhasil menyerang balik. Salman berdecak.
“Apaan sih, Mom.” Lalu memalingkan muka setelah ditatap lurus dan lekat oleh Mommy-nya. Dia bisa membaca ada harapan besar yang menyala-nyala dari kedua mata berembun itu. Jujur, pasang mata itu membuat hatinya sedikit lintuh.
“Mommy yakin kamu adalah anak Mommy dan Daddy yang terpilih untuk mengemban amanah mulia ini. Tidak usah iri dengan Kak Yujin. Kasih sayang Mommy dan Daddy ke kalian itu sama. Dulu kamu udah nolak terus masuk ke pesantren. Mommy harap kali ini kamu nggak nolak lagi dan Opa bisa tenang di sana.”
“Tapi mana bisa kuliah sambil mondok?” protes Salman lagi.
“Bisa kok. Ada pesantren deket kampus yang nampung ratusan mahasiswa. Mommy udah survei kemarin sama Tante Hani. Asyik malah kayaknya kuliah sambil mondok. Kalau saja waktu bisa diputar Mommy pengen kuliah sama mondok.”
“Emang pesantrennya bolehin bawa hape?” tanya Salman keheranan.
“Laptop juga boleh. Gimana ngerjain tugas kuliahnya kalau nggak boleh bawa dua benda itu?” Mommy mengerling. Salman tampak menimbang-nimbang.
“Mobil juga?” tanya Salman.
Kali ini Mommy berdecak. “Latihan prihatin aja dulu, Ris. Bawa motor aja.”
“Nggak mau,” tolak Salman mentah-mentah. Mana ada tuan muda naik motor? Apa kata dunia anak kedokteran bawa motor ke kampus? Apalagi yang ganteng “nggak ada obat” seperti dirinya?
“Belajarlah sederhana. Karena kesederhanaan itu membuat hati tentram,” ujar Mommy. “Daddy aja yang udah CEO nggak gengsi pake sarung,” sahut lelaki yang tiba-tiba muncul sambil menenteng tas kerja.
“Malah tambah ganteng ya kan, Dad?”
Lelaki yang dipanggil Daddy itu mengangguk. “Mommy-mu aja awal jatuh cinta sama Daddy pas Daddy pake sarung,” imbuh Daddy dengan ekspresi bangga. Dan Salman ingin muntah.
“Apaan sih, Dad,” ujar Mommy tersipu.
“Tapi aku nggak bisa kalau disuruh hafalin Al-Qur’an,” sungut Salman lagi. Tapi kalimat itu sukses membuat Mommy-nya berbinar karena merasa Salman memberi lampu kuning.
“Ya udah nggak apa-apa. Mau mondok aja Mommy udah seneng. Dicoba dulu, Okey?”
“Bentar deh, Mom. Aku selama ini nggak pernah bikin ulah, kan? aku bahkan selalu berprestasi selama SMP dan SMA. Aku nggak pernah neko-neko atau bikin kasus di sekolah. Kenapa aku harus masuk ke pesantren? Mommy keberatan aku minta rumah yang deket kampus?”
Rupanya Salman tak bisa ditaklukkan begitu saja.
“Loh, memangnya yang masuk pesantren itu harus anak-anak bandel ya? bibit-bibit sisa? Gimana coba kualitas para ustadz dan dai nanti. Apa bisa generasi Indonesia semakin berkualitas kalau dipimpin orang-orang seperti mereka? Kamu nggak kasihan dengan nasib umat Islam nanti?”
Akhirnya Salman berhasil memancing Mommy-nya untuk berbicara dengan nada sedikit meninggi. Bahkan keningnya berkerut-kerut masygul. Membuat kepala Salman terasa melayang.
“Mommy pengen punya anak lelaki seperti Ibnu Rusyd. Ahli hukum Islam dan kedokteran,” kata Mommy pelan-pelan.
“Daddy sanggup kok belikan kamu rumah mewah dekat kampus. Tapi Daddy tidak mau melakukannya karena Daddy pengen kamu belajar kesederhanaan. Daddy tidak mau kamu tergelincir ke dalam pergaulan bebas.” Daddy menimpali. Salman mengerjap-ngerjap. Lehernya terasa layu.
“Mommy mohon dengan sangat kamu mau masuk pesantren supaya pesantren ada bibit unggul calon ulama dan dokter nanti.” Kalimat Mommy sukses membuat Salman merinding.
Setelah beberapa detik, tak ada jawaban lagi. Itu artinya Mommy dan Daddy menang. Give applause to Daddy and Mommy.
“Setelah itu Mommy nggak bisa ngatur aku lagi ya?” Salman mengajak bernegoisasi.
“Maksudmu?” Dahi Mommy berkerut.
“Mommy nggak boleh jodoh-jodohin aku. Aku bisa milih sendiri siapa calon istri aku nanti,” pungkasnya sambil bangkit. Ia tak mau dengar apapun lagi respon dari Mommy karena ya … tidak perlu direspon. Mommy cukup mengangguk setuju. Seperti yang dilakukannya saat ini. Dia cukup patuh pada Qismul Amni dan mengikuti langkah mereka menuju ndalem. Sebenarnya ini perintah Bu Nyai Maryam. Makanya Salman semangat.
Dia bahkan tersenyum-senyum selama perjalanan. Itu karena dia baru saja mendapat info lumayan lengkap mengenai Bu Nyai Maryam dari Kang Burhan—senior dari fakultas hukum. Entah data yang diberikan Kang Burhan valid atau tidak. Yang jelas lelaki dari Madura itu terlihat tulus dan tidak pernah menggodanya seperti yang lain. Jadi, Salman percaya.
“Nyai Maryam itu konon santri putri Al-Mukmin,” terang Kang Burhan.
“Kok konon? Konon tuh buat legenda nggak sih? Nggak nyata,” protes Salman.
“Ya ini dari kabar yang berhembus turun-temurun. Aku hanya ngasih berita yang aku tangkap aja.”
Salman manggut-manggut. “Oke-oke. Lanjut, Cak.”
“Jadi Ummah Maryam itu selain cantik, juga sangat cerdas. Dia adalah santri yang paling berprestasi di Al-Mukmin. Hingga membuat Abah punya keinginan menjadikan Ummah Maryam istri keduanya dan memintanya memimpin pondok cabang yang kita tempati ini. Santri Al-Mukmin yang membludak setiap tahunnya menjadikan pondok pusat overload dan tidak kuat lagi menampung santri. Sedangkan putri tertua Abah, Ning Najila sudah fokus di pusat bersama Abah dan Ummi.”
“Ning siapa tadi putrinya Abah? Najiya?” Salman merasa tidak asing dengan nama itu.
“Najila bukan Najiya,” jawab Kang Burhan.
“Oooh. Terus Ummi Shafiya setuju aja dipoligami?” tanya Salman dengan nada tak terima.
Kang Burhan tampak merenung sebentar sebelum menjawab, “Sejauh pengamatanku ya beliau ikhlas aja kok. Mungkin orientasinya surga.”
“Banyak jalan menuju surga, Bro. Nggak harus mengorbankan perasaan juga.” Salman masih kekeh dengan keidealisannya.
“Ya nggak tau, prinsip orang kan beda-beda,” sahut Kang Burhan enteng.
“Gue nggak yakin Ummi Shafiya bener-bener ikhlas, seyakin aku kalau Ning Maryam juga nggak ikhlas dimadu. Pasti ada sesuatu di balik semua ini.” Selain gemblung, penyakit Salman lainnya sepertinya adalah sok tahu dan keminter.
“Bu Nyai Maryam. Panggil dia Ummah. Ning itu untuk putri Kiai, Cung,” tegur Kang Burhan meluruskan bagaimana cara Salman tadi memanggil Nyai Maryam.
“Nggak mau dia masih muda. Kasihan kalau udah dipanggil Nyai. Risih aku denger sebutan Nyai. Kayak Nyai Ronggeng.”
Tawa Kang Burhan langsung menyembur. “Bocah gendeng pancen,” decaknya sambil menjitak kepala Salman.
“Oh ya, Ummah Maryam itu juga masih kuliah. Dia anak bahasa di Sultan Ageng.”
Salman langsung terlonjak saking kagetnya. “Yang bener? Bisa ketemuan di kampus dong?” sahutnya kurang ajar.
“Terus kalau bisa ketemuan di kampus, mau kamu apakan?” tanya Kang Burhan mulai geregetan. Dia saja bersama santri putra lainnya hanya bisa meneropong dari kejauhan kalau Bu Nyai Maryam melintas.
“Mau aku ajak makan bareng lah di kantin.”
“Bocah edaaaaan,” hardik Kang Burhan. Dan Salman langsung lari terbirit-birit menghindari pukulan dari Kang Burhan.
Yes … yes …. Salman masih terpekik-pekik sendiri dalam diam. Ia seperti mendapat rezeki nomplok saat tahu Nyai Maryam juga kuliah di kampus yang sama dengannya. Dia semakin tidak sabar bertemu dengan perempuan kedua Kiai-nya itu. Duduknya semakin tidak tenang saat sudah berada di ruang tamu ndalem bersama para pengurus. Pengurus resah dan berharap Nyai Maryam mengurungkan untuk interogasi dan tabayun malam ini, Salman justru sebaliknya. Dia menginginkan Nyai Maryam segera muncul di hadapannya.
Salman masih mengetuk-etukkan ujung jari pada karpet saat sebuah suara tiba-tiba terdengar.
“Salman come here, Please. Salman my sweety. Sayaaang ….”
Leher Salman langsung tegak. Pasang matanya membola dan tubuhnya seperti disengat listrik setelah yakin siapa pemilik suara itu. Apa? Nyai Maryam memanggilnya sayang? Ia jelas tidak siap dengan respon yang terlalu cepat ini. Ah, ternyata pesonanya memang terlalu sulit untuk ditampik perempuan mana pun.
“Salman … my sweety. Come here ….”
Lagi. Suara itu terdengar. Para pengurus seperti tengah kesulitan menahan tawa. Mereka terkikik-kikik hingga suaranya seperti tikus terjepit pintu.
“Kang, kamu dipanggil tuh,” ucap salah satu pengurus sambil mengulum senyum.
Salman tertegun. Ia bimbang, galau, blushing, atau … apalah itu. Intinya pantatnya sudah tidak seperti menapak karpet.
- Penulis: admin







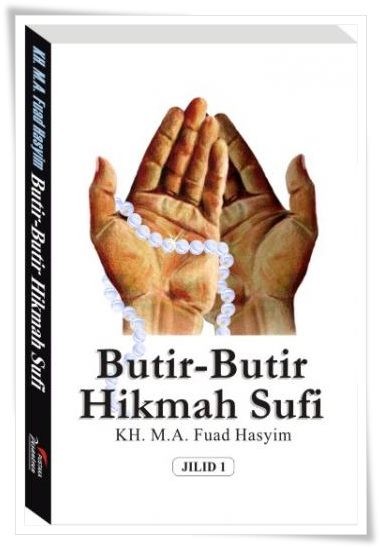







Saat ini belum ada komentar