Rapat Tikus di Kamar Bersalin
- account_circle admin
- calendar_month Ming, 5 Feb 2023
- visibility 179
- comment 0 komentar
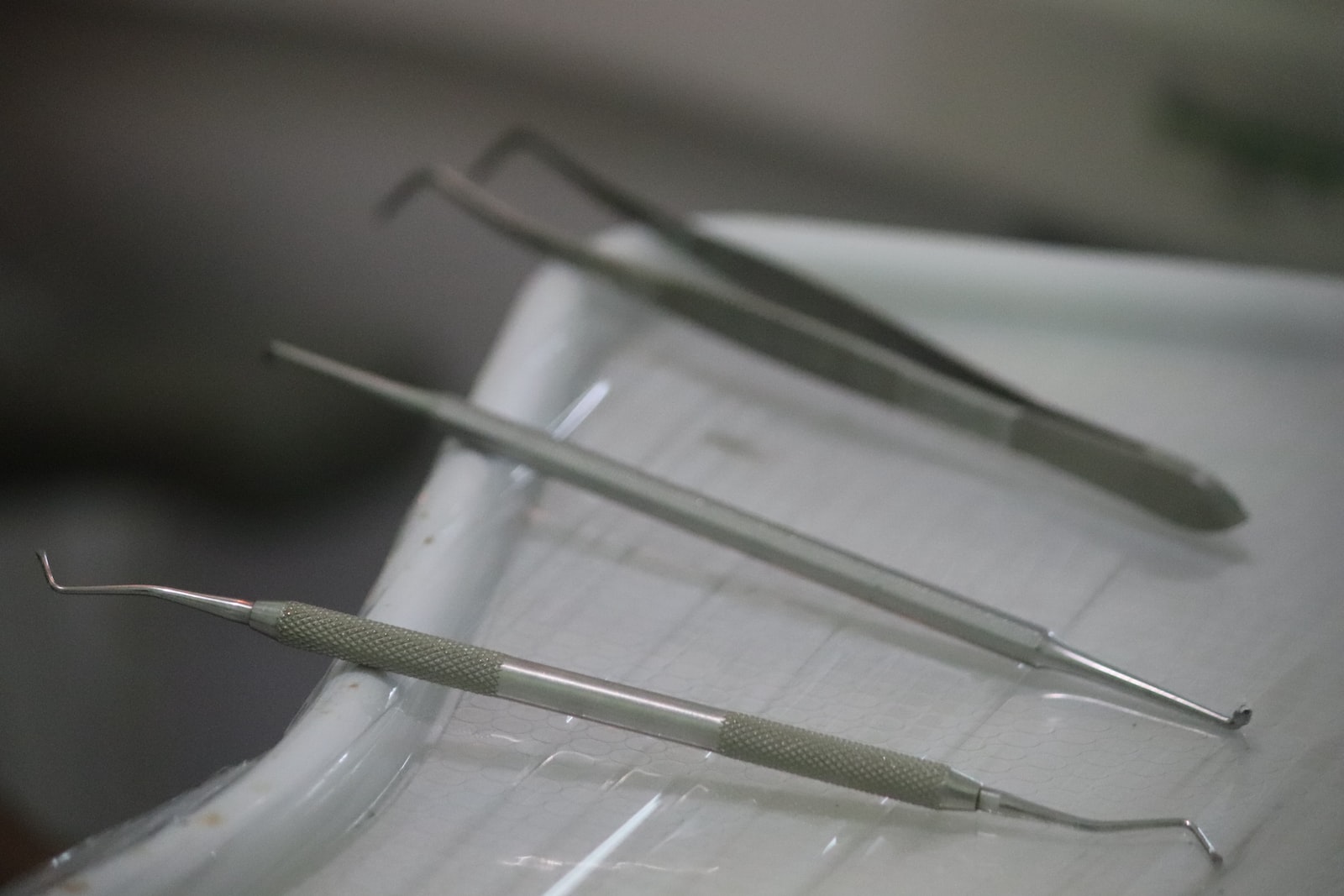
PCNU-PATI Photo by Mufid Majnun
Oleh : Elin Khanin
“Kalau nggak pergi, aku teriak nih.”
Shanaya mendekap sebuah bantal dan siap menimpukkan bantal itu ke arah Nikhil. Sudah hampir tengah malam dan sedang tidak ada pasien di RB. Jadi suasana rumah bersalin kali ini sangat sepi. Bisa dipastikan Tita dan Bu Eko sudah lelap di tempat peristirahatan masing-masing. Tubuh Shanaya masih menegang waspada. Ia sudah mengambil ancang-ancang jika lelaki yang duduk di pojok kamar dekat ranjangnya berbuat macam-macam. Tapi tetap saja ia masih disergap rasa yang entah. Rasa tak percaya, terkejut, bahagia, jengkel berbaur menjadi satu. Ia ingin memekik senang tapi juga ingin berteriak kesal. Ia tak tahu harus bersikap bagaimana sekarang. Mungkin jutek adalah sikap yang tepat untuk saat ini.
Ini beneran Nikhil visualku, ‘kan? jangan-jangan ini mimpi? Huaaa, Juan … please jemput aku sekarang juga!
Napas Shanaya sejenak sedikit engap akibat rasa yang meletup-letup dalam dadanya.
“Dengar, Shanaya ini nggak seperti yang kamu kira. Aku datang mau meluruskan sesuatu. Kita bisa bicarakan ini baik-baik.” Nikhil melirihkan suaranya.
“Gimana bisa orang asing kayak Alien tiba-tiba datang terus ngaku suami?” Shanaya mendengkus kesal. Ia memijit pelipisnya. Kepalanya masih sedikit pusing. Wajahnya serasa terbakar.
Nikhil menghirup napas sejenak sebelum menyahut lagi dengan suara lirih. “Kita memang sudah menikah.”
Pasang mata Shanaya seketika membola.
“Kamu jangan aneh-aneh ya?”
“Ini benar, Shanaya. Tadi sore akadnya. Akad dadakan dengan persiapan ala kadarnya. Di musholla depan rumahmu hanya dihadiri keluarga dekat.”
Nikhil menunjukkan foto di ghallery handphone-nya. Shanaya mendekat dan menyambar handphone milik Nikhil. Ia amati lamat-lamat foto itu. Disitu ada dua orang lelaki sedang berjabat tangan di atas meja kecil yang dilapisi kain seperti melakukan sesi ijab qabul. Nikhil benar-benar menjabat tangan Ayahnya. Beberapa kali Shanaya mencocokkan lelaki di foto dengan lelaki yang duduk di hadapannya. Lelaki ini tidak bohong.
“Tapi … bagaimana bisa?”
“Bukankah kamu sudah menyetujuinya?”
“Aaaahhh … aku pasti sudah gila. Ayah benar-benar gila. Aku nggak benar-benar bersedia. Aku hanya di posisi yang serba sulit hari ini.”
“Ya, aku juga gila. Kita adalah keluarga gila,” ujar Nikhil setengah bergurau setengah serius. Shanaya memutar bola mata.
“Bisakah kita bicara di luar saja?” lanjutnya memasang sikap waspada. Berkali-kali ekor matanya melirik jendela kaca yang gordennya terbuka.
Shanaya mendelik.
“Aku bersumpah nggak akan berbuat macam-macam,” songsong Nikhil seperti tahu isi kepala Shanaya.
“Nggak mau. Bicara saja di sini!” Shanaya menjulurkan leher ke jendela. Sepi. Hanya terdengar gemericik air kolam dari taman kecil di pojok ruang tunggu. Lampu-lampu remang-remang telah mengganti lampu utama. Ia masih disergap rasa was-was.
“Asal kamu tahu. Aku terpaksa melakukan ini.”
“Oh ya? Terus kamu pikir kamu saja korban dari pempleoncoan ini?” Shanaya melotot.
“Bukan begitu.”
“Apa motif kamu mau menerima pempleoncoan ini?” tuntut Shanaya.
“Ceritanya panjang. Shanaya, aku nekat kesini agar bisa menemuimu dan bicara berdua saja tanpa ada gangguan dari pihak keluarga. Mereka, orang tua kita sedang berembuk menyiapkan pernikahan resmi untuk kita.”
Shanaya masih tak habis pikir. Takdir macam apa ini?
“Ini semua salahmu! Kenapa kamu mau saja dijadikan boneka mereka. Uuuuuhhh.”
“Sudah kubilang aku terpaksa. Aku juga berada di posisi serba sulit.”
“Sesulit apa hingga kamu nekat nikah dadakan?”
“Oke … dengar ceritaku baik-baik.”
Nikhil menghirup napas sejenak sebelum memulai ceritanya. Ia berharap Shanaya mau memahami dan berkompromi sesuai rencananya.
————–
“Maafkan aku, Kak Nikhil. Aku nggak bisa melawan kehendak Romo. Aku lebih pantas dijuluki robot, bukan seorang anak. Darah biru itu sialan sekali,” kesalnya dengan suara lirih.
Segera ia usap air mata yang menitik di pipinya dengan tisu. Wajahnya yang sembab tertunduk dalam, mungkin takut diketahui banyak orang yang sedang berlalu lalang. Atau mungkin karena tidak berani menatap wajah lelaki yang duduk di sampingnya. Ia juga takut jika menatap wajah bagai pangeran Lee Pyo di drama Moonshine itu hatinya akan semakin goyah.
Kawin lari tentu bukan solusi yang baik. Dia bukan tipe seperti itu—yang rela melakukan apa saja atas nama cinta. Dia adalah gadis yang ketika bicara akan membuat orang menyurukkan wajah dan mendekatkan telinga. Suaranya lembut bagai nyanyian seruling. Tindak tanduknya seperti putri-putri keraton. Mungkin karena memang dilahirkan dari keluarga bangsawan dan darah ningrat yang mengalir di tubuhnya, ia tumbuh menjadi gadis yang bahkan digigit nyamuk saja bisa pingsan. Nyimas Ayu Safira. Begitu orang tuanya memberi nama. Panggilannya Ayu seperti orangnya.
“Jangan mencela sebuah gelar. Itu kan anugerah, sebuah kemuliaan. Mungkin aku yang salah sudah berani mendekatimu. Aku yang salah, Yu.”
Lelaki itu mengerjap cepat beberapa kali, berusaha menghalau kaca-kaca yang hendak jatuh dari netranya. Mana pantas seorang lelaki gagah seperti perwira sepertinya menangis. Meskipun hatinya sakit bagai diiris-iris sebuah belati, ia tidak boleh terlihat menyedihkan.
“Ayu hanya mencintai Kak Nikhil seorang. Apapun yang terjadi. Ingat itu!”
Jika tidak ingat sedang dimana, ingin sekali Nikhil memeluk gadis di sampingnya. Jika bukan untuk memberikan ketenangan atau meluapkan perasaan cinta, mungkin sebagai pelukan perpisahan. Karena dua minggu lagi Ayu akan menikah dengan lelaki bergelar ningrat seperti dirinya. Bukan lelaki pribumi biasa seperti Nikhil.
Lelaki itu menghembuskan napas berat sebelum menyahut. “Semoga Ayu bahagia.”
Dua tahun yang lalu, di bawah pohon beringin yang dahannya bergoyang-goyang ditiup angin sore, cinta itu terucap. Sebuah sumpah akan saling setia sehidup semati telah terpatri. Kini di bawah pohon yang sama, cinta dan sumpah bagai pohon beringin tua yang mengelilingi alun-alun Wonomukti harus tumbang dalam sehari. Segala bentuk perjuangan mempertahankan cinta dan sumpah selama dua tahun itu berbuah nestapa. Hancur dalam sekejap mata. Ternyata pernikahan sesama darah biru itu bukan rumor belaka. Sekarang Nikhil menyesal kenapa dulu tak mengindahkan nasehat orang tua dan hande taulannya.
“Nang, sebaiknya jangan berhubungan dengan Ayu. Dia itu dengar-dengar darah biru ya? konon darah biru itu nikahnya harus sama yang darah biru. Kita harus tahu diri, Nang,” ucap Sang Ibu.
“Ojo pacaran sama orang darah biru loh. Mereka biasanya cuma mau nikah sama yang darah biru,” celetuk Rahmat sahabatnya.
“Kamu kok berani ndekati Ayu to, Nik. Dia kan darah biru.”
Nasehat-nasehat itu berdengung-dengung di telinganya. Beriringan dengan wajah kekasihnya setiap menit, setiap detik. Pesona Ayu begitu sulit ia lenyapkan dari kepalanya. Berhari-hari setelah perpisahan itu, Nikhil seperti kehilangan semangat hidup. Ia hanya mengurung diri di kamar. Itu membuat Ibunya bingung bukan kepalang. Segala bentuk nasehat seperti tak ada guna. Tapi Ibunya tak berputus asa. Ia terus berusaha menyentuh hati putranya. Berbicara lirih di depam pintu kamar.
“Nang … dunia tidak akan kiamat hanya karena putus cinta,” ujarnya hati-hati.
“Masih banyak di luar sana gadis yang baik yang mau sama kamu. Ini putrinya Pak Ridwan, temannya Bapak juga ayu, kuliah di kebidanan juga. Pak Ridwan mau putrinya nikah secepatnya. Ibu akan senang sekali kalau kamu mau,” bujuk Bu Tutik, Ibu Nikhil.
“Baiklah, aku mau. Tapi nikahnya hari ini juga,” seloroh Nikhil dari dalam kamar dengan perasaan putus asa tingkat dewa.
- Penulis: admin
















Saat ini belum ada komentar