Ilusi Kaum Kota: Slow Living di Desa
- account_circle admin
- calendar_month Kam, 6 Feb 2025
- visibility 311
- comment 0 komentar

Oleh: Maulana Karim Sholikhin*
Desa memang cenderung lebih unggul dibandingkan kota dalam urusan kualitas udara. Jumlah kendaraan berbahan bakar fosil dan industri makro yang sedikit menjadikan desa tempat yang baik untuk bernapas. Masyarakatnya juga punya kepedulian tinggi dan ramah-ramah. Gedung-gedung belum menjamah sampai ke sana, sehingga view alamnya lebih natural, tanpa solek bangunan tinggi.
Nilai plus lain, Cost hidup di desa sangat terjangkau bagi kalangan berpenghasilan ‘kota’. Makanan, minuman hingga harga tanah akan jauh lebih murah daripada kota dengan komposisi dan ukuran sama. Gaji UMR mungkin butuh waktu hingga ratusan tahun untuk menabung guna membeli sebidang tanah di kota. Akantetapi dengan ukuran yang sama, tanah di desa bisa berpuluh kali lipat lebih terjangkau, sehingga bisa menghemat waktu menabung.
Inilah mengapa trend slow living tinggal di desa menjadi booming. Pesona desa yang tersebar lewat tiktok dan instagram serta memori manis ketika KKN, melahirkan kembali nostalgi nan melankoli, betapa romantiknya jika desa digunakan sebagai destinasi menghabiskan usia.
Hanya saja, sebagai orang yang lahir, tumbuh besar di desa dan pernah merasakan kerasnya kota besar dalam waktu relatif lama, penulis bisa mengomparasikan keabsud-an masyarakat kota maupun desa.
Hidup di sini (baca: desa) memang sangat tricky. Bukan urusan perut dan ekonomi, namun lebih pada fakta sosial. Tinggal di desa untuk selamanya tak bisa dibanding dengan peristiwa manis selama KKN yang hanya satu atau dua bulan. Desa menggenggam tantangannya sendiri, begitupun kota. ‘Kekejaman’ desa tak ubahnya kerasnya kota dalam kemasan sachet dengan rasa yang berbeda.
Pertama, masyarakat desa ancap kali memiliki rasa ingin tau yang tinggi, bahkan sampai merogoh ranah prifasi individu lain. Dengan kata lain, sekat antara A dan B hanyalah garis ilusi. Para hidung belang, jangan harap bisa selingkuh di sini, sebab semua warga akan tahu.
Ke dua, bertautan dengan fakta pertama, kemampuan menganalisa masyarakat desa sangatlah tajam, penggalian data dilakukan secara masif dan canggih. Kita tidak bisa bersembunyi dari mereka, sebab ‘CCTV’ yang terorganisir–seperti bekerja dengan cara magis–bisa mengawasi segala yang kita punya dan kita alami.
Sayangnya, kemampuan ini tidak diiringi dengan pengolahan data dan pengambilan simpulan yang baik, keduanya kacau!. Hal ini terjadi lantaran ‘riset’ yang mereka lakukan amatlah subjektif. Apriori bahwa objek penelitian harus selalu salah, sekaligus menjadi simpulan tanpa pengolahan data terlebih dulu. Sebab, informasi aib lebih laku di pasaran.
Ke tiga, arus informasi, terutama dikalangan emak-emak sangatlah deras. Sebelum ditemukannya jaringan 5G, pasar, sawah, kang sayur sudah menjadi ruang pertukaran informasi dengan kecepatan cahaya. Karenanya, aib yang berhasil dicitrakan akan menyebar liar tanpa kendali dan tidak akan berhenti sebelum seisi desa mengetahui
Ke empat, daya saing masyarakat desa juga lebih tinggi dibandingkan masyarakat kota. Kompetisi selalu terjalin ketat diantara mereka. Ketika satu KK membeli televisi berukuran 41’’, tetangga sebelah melonjak adrenalinnya untuk membeli 52’’. Seorang suami membelikan isterinya sepeda motor, maka isteri tetangga—entah dengan cara apa—juga harus memiliki motor yang sama. Begitu pula dalam urusan fashion sampai teflon untuk menggoreng telur, jika dia punya, akupun harus punya!.
Ke lima, masyarakat desa tanpa disadari menganut marxisme dalam urusan penyetaraan (kecuali kalangan elit desa seperti tuan tanah, ASN, pengusaha atau alumni perantauan Jepang-Korea, mereka punya kelasnya sendiri). Masyarakat bawah yang tampil wah, akan menimbulkan beragam asumsi. Namun segala probabilitas yang muncul tak akan kemana-mana, masih dalam tema: dicurigai memelihara tuyul, babi ngepet atau pesugihan.
Ke enam, Masyarakat desa juga cukup diskriminatif khususnya terhadap kaum miskin. Misal, dalam urusan hajatan saja, orang-orang miskin yang hadir gercep, dicap cari makan gratis. Kalaupun mereka terlambat datang, maka dicap tidak tau diri, kalau mereka tidak datang, apalagi.
Inti dari segala inti, tidak semua warga desa memiliki karakteristik seperti disebutkan tadi, dan tidak ada niatan untuk mendiskreditkan desa (sebab penulis juga orang ndeso). Meski demikian, narasi tersebut bisa dikatakan mendekati valid. Karena, tulisan ini merupakan simpulan dari puluhan bahkan ratusan cerita dari teman-teman yang mukim di desa, dan beberapa diantaranya adalah pengalaman penulis sendiri.
Terakhir, jadikan desa hanya sebagai tempat singgah setiap weekend agar warga metropolitan tidak perlu mumet memikirkan risiko yang harus dihadapi, sekaligus tidak ‘mencemari’ budaya ndeso dengan style kota yang individualis dan materealis. Ujungnya, di desa maupun di kota, slow living selalu bisa digapai hanya dengan mindset stoik yang kuat.
*penulis merupakan pendidik di Ponpes Shofa Az Zahro’ Gembong-Pati
- Penulis: admin






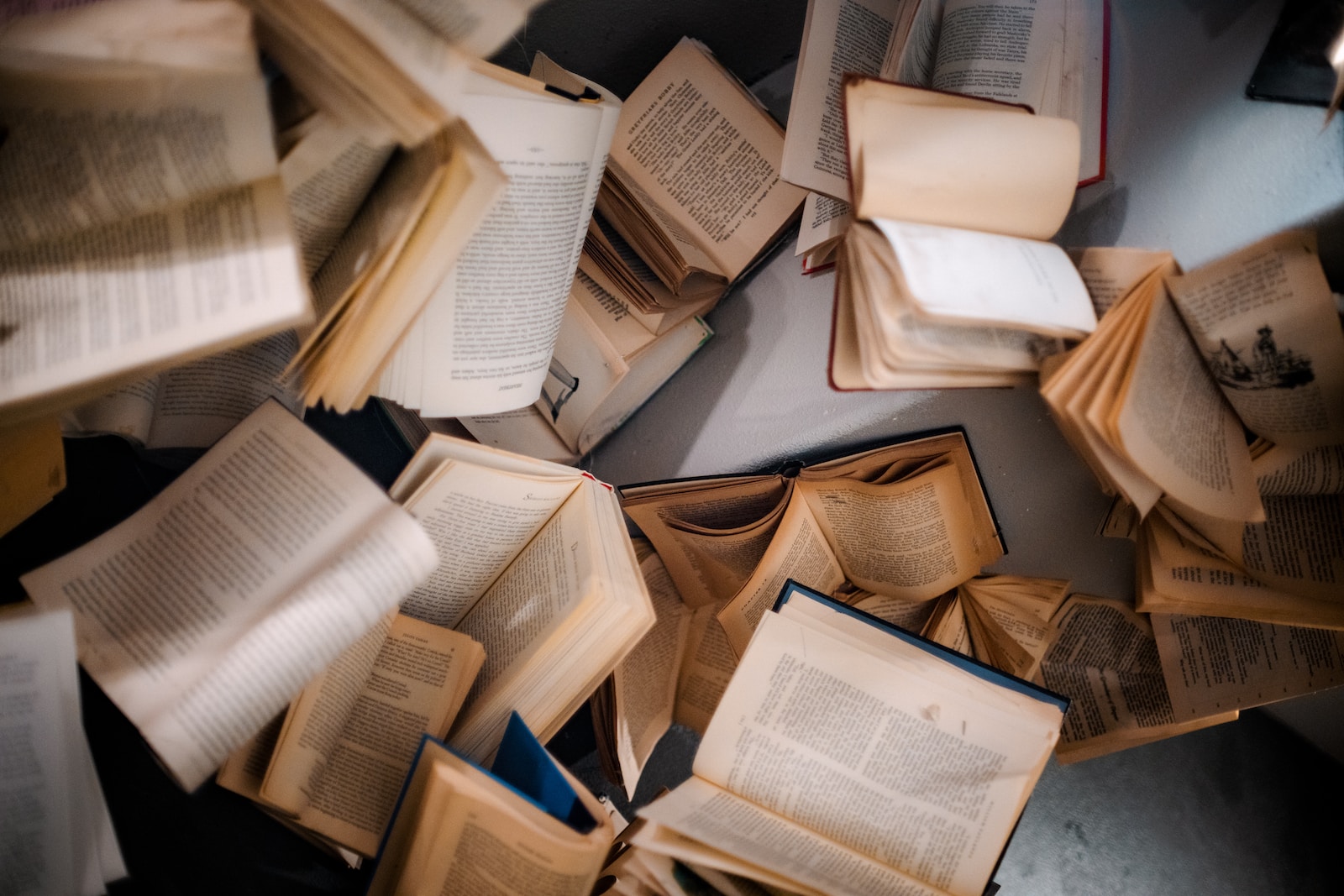





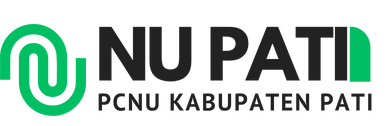
Saat ini belum ada komentar